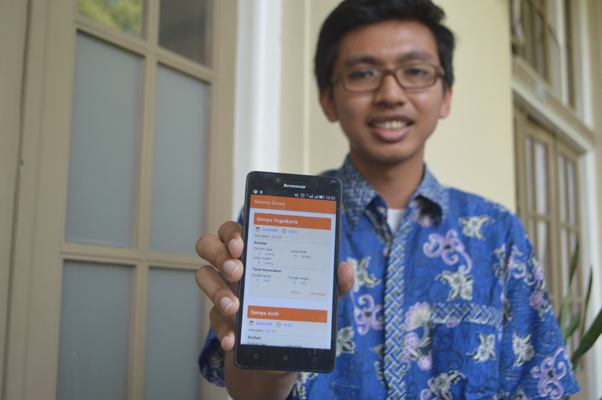Gempa bumi berkekuatan 5,9 Skala Richter yang melanda DIY dan Jawa Tengah pada 27 Mei 2006 silam mengakibatkan 5.749 korban meninggal, 428.909 rumah penduduk rusak berat atau roboh, dan menimbulkan total kerugian sekitar Rp29,2 Triliun. Sejak peristiwa tersebut upaya pengurangan risiko bencana telah menjadi bagian penting dalam program pembangunan yang dilakukan di semua sektor.
Besarnya dampak yang timbul dalam peristiwa ini menunjukkan ketidaksiapan pemerintah pada saat itu dalam menanggulangi potensi gempa di wilayah DIY. Namun, pasca peristiwa tersebut proses pemulihan dan pembangunan berlangsung relatif cepat. Dalam jangka waktu 253 hari, sebanyak 144.034 rumah yang roboh atau rusak berat telah dibangun kembali, atau dengan kata lain, rata-rata 570 rumah dibangun setiap harinya.
“Salah satu hal yang berhasil kita gali dalam diskusi yang berlangsung sebelum ini adalah bahwa kita memiliki modal yang cukup kuat, yaitu kebudayaan. Hal ini menjadi pondasi bagi masyarakat DIY untuk bisa pulih kembali seperti semula,” ujar Kepala Pusat Studi Bencana (PSBA) UGM, Dr.Rer.Nat Djati Mardiatno, M.Si, dalam sarasehan Kilas Balik Pembangunan Pasca Gempa Bumi Yogyakarta – Jawa Tengah 2006, Rabu (25/5) di PSBA UGM.
Terkait hal ini, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, Gatot Saptadi, menjelaskan 4 faktor yang menentukan keberhasilan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempan yang kesemuanya bersumber dari kearifan masyarakat Yogyakarta. Keempat hal ini adalah kepemimpinan, penerapan kearifan lokal, pemberdayaan masyarakat secara benar, serta nilai-nilai kehidupan masyarakat, seperti budaya tolong-menolong dan saling menghargai.
Lebih lanjut Gatot menjelaskan bagaimana dalam proses ini masyarakat mampu bekerja sama dengan pemerintah. “Proses pemulihan ini konsepnya community-based. Pemerintah memberikan stimulan sebesar Rp15 juta per rumah, dan masyarakat rata-rata berkontribusi sebesar Rp28,10 juta, baik dalam bentuk dana, tenaga kerja, material, serta berbagai peralatan bangunan,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Bidang Advokasi Forum Pengurangan Risiko Bencana DIY, Aris Sustiyono, menyampaikan bahwa pengalaman ini memberikan pelajaran bahwa pembangunan di DIY perlu memperhatikan faktor budaya masyarakat.
“Masyarakat DIY sejak dulu kala dikenal memiliki sebuah tradisi dan pengetahuan adiluhung mengenai tata kelola kehidupan masyarakatnya. Hal ini mestinya dapat menjadi satu pegangan atau prinsip pembangunan yang dianut agar arus modernisasi tidak serta merta menghapus pengetahuan/kearifan lokal yang sudah ada sebelumnya,” paparnya.
Salah satu nilai yang disebutkan yaitu falsafah hidup yang dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwana I, Hamemayu Hayuning Bawana, yang dapat diartikan sebagai bentuk hubungan yang harmonis, baik antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, maupun manusia dengan alam sekitarnya. Prinsip ini, menurutnya, harus diterjemahkan ke dalam kebijakan pembangunan yang tetap mengakar kuat pada kearifan budaya lokal, khususnya di tengah laju perkembangan pembangunan di DIY yang menimbulkan kompleksitas permasalahan.
“Menjadi modern tidak harus meninggalkan falsafah hidup yang diajarkan oleh nenek moyang kita, karena sejatinya falsafah adalah cara pandang ke depan dalam meniti kehidupan ini,” tambahnya. (Humas UGM/Gloria)