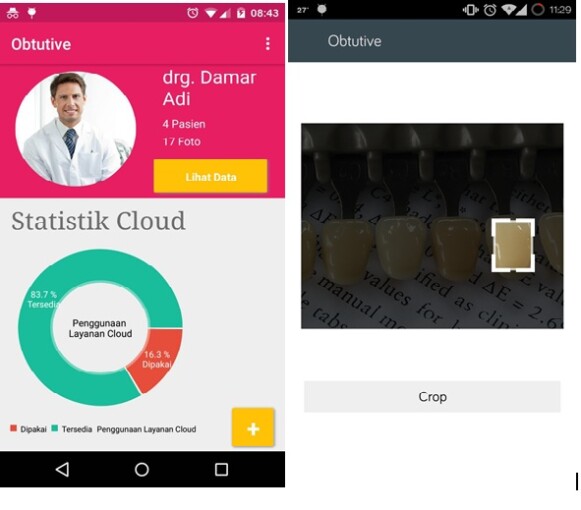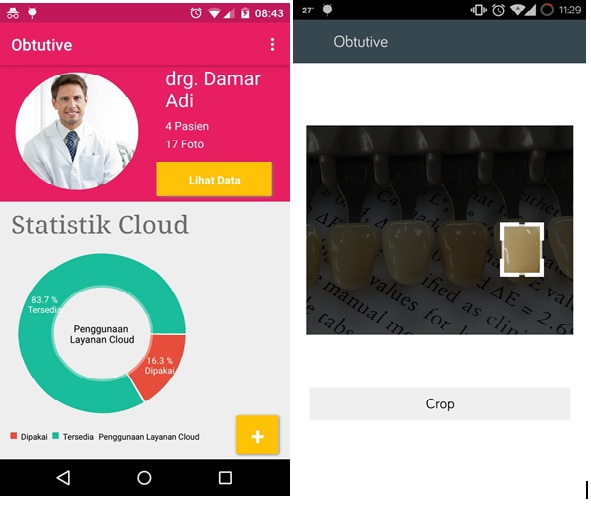Suasana Idul Fitri di Kabupaten Tolikara, Papua belum lama lalu sempat terusik dengan berita kerusuhan yang menyebabkan satu orang meninggal dan belasan terluka karena tembakan aparat serta puluhan kios dan sebuah mushola di dekatnya terbakar.
Direktur CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies), Sekolah Pascasarjana UGM, Dr. Zainal Abidin Bagir melihat setiap ada konflik yang melibatkan atau menggunakan simbol-simbol agama dan mengenai umat beragama, hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa setiap konflik tidak pernah memiliki hanya satu sebab tunggal. Setiap konflik biasanya memiliki banyak penyebab.
“Konflik agama tidaklah sepenuhnya mengenai agama. Dalam laporan CRCS mengenai Politik Lokal dan Konflik Keagamaan, semua konflik keagamaan yang dibahas menunjukkan ciri itu, misalnya bertemunya kepentingan politik lokal dengan (manipulasi) simbol keagamaan,” urai Zainal, Kamis (23/7).
Zainal mengatakan dalam kasus di Tolikara, konteks penting adalah kompleksitas dan kerentanan persoalan Papua pada umumnya. Kerentanan ini, seperti bisa dilihat dalam beragam kasus-kasus non-agama lainnya di Papua, kerap direspon oleh aparat keamanan secara represif dengan menggunakan senjata untuk melukai atau membunuh. Secara lebih khusus, Kabupaten Tolikara sendiri cukup rawan-politik, seperti tampak dalam konflik di sekitar Pilkada pada Februari 2015.
“Maka hal remeh, seperti soal speaker bisa dengan mudah meletuskan konflik kekerasan, bahkan merenggut korban jiwa di sana,” katanya.
Dalam pandangan CRCS, kata Zainal, isu utama “kerawanan Papua” sesungguhnya jauh dari agama. Dalam Papua Road Map, misalnya, yang merupakan hasil kajian LIPI (2008), ada empat masalah utama yang diidentifikasi sebagai akar persoalan Papua, dan di sana, agama sama sekali bukan sumber masalah. Dalam konteks ini salah satu contoh yang bisa diambil adalah Pater Neles Tebay, seorang pemimpin Katolik yang dikenal juga sebagai Koordinator Jaringan Damai Papua. Dalam pernyataannya mengenai insiden di Tolikara, Pater Neles mengungkapkan, budaya Papua tidak mengajarkan orang untuk mengganggu, apalagi membakar tempat ibadah.
“Diskusi pada tahun 2013 yang diselenggarakan Program Studi Agama dan Lintas Budaya UGM (CRCS) bersama STAIN Papua dan melibatkan tokoh-tokoh agama, yang muncul justru adalah peran agama sebagai sumber modal sosial untuk perdamaian,” imbuh Zainal.
Di Papua, sesungguhnya sumber polarisasi yang lebih penting bukanlah agama, namun antara pendatang dan orang asli Papua. Polarisasi yang tak sehat ini mewarnai kehidupan sosial dan ekonomi, dan sebagiannya muncul dalam UU Otonomi Khusus Papua. Politik identitas yang memberikan keistimewaan pada orang asli Papua dapat bermakna baik jika dipahami sebagai affirmative action, namun dapat pula menjadi penegasan polarisasi yang terlalu jauh. Yang menarik, polarisasi itu bahkan muncul dalam kelompok-kelompok dalam suatu agama tertentu. Ada ketegangan dan klaim-klaim identitas yang dibuat untuk membedakan Kristen pendatang dan Kristen asli Papua; juga antara Muslim Papua dan Muslim pendatang.
Kembali ke kasus Tolikara, sumbangan terkecil adalah tidak memperburuk situasi dengan menjadikan kasus ini sebagai bahan provokasi. Yang diperlukan adalah arus informasi yang positif, bukan yang membakar. Khususnya untuk kita yang berada di luar Papua, baik Muslim ataupun Kristen, klaim-klaim keagamaan yang dibangkitkan dengan menjadikan kasus Tolikara sebagai pembenaran mungkin hanya bermanfaat untuk kepentingan kelompok sendiri, bukan untuk kepentingan saudara-saudara kita di Papua.
“Papua telah kerap menjadi arena tindakan kekerasan, maka pendekatan dialogis harus diprioritaskan. Tanpa itu, sulit bagi kita untuk berbicara mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas Zainal. (Humas UGM/Satria)