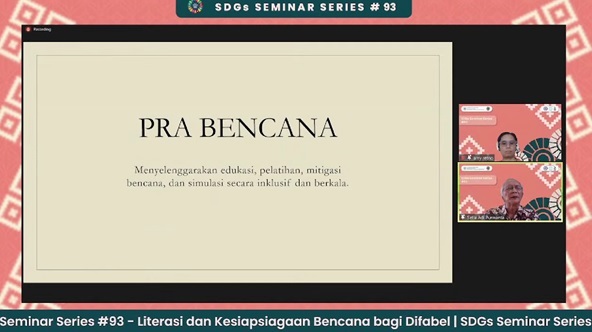
Mitigasi bencana merupakan salah satu isu yang turut menjadi bagian dari rencana pembangunan berkelanjutan atau Suistanable Development Goals (SDGs). Mengingat datangnya bencana yang bisa datang kapan saja, upaya pengembangan sistem mitigasi sangat diperlukan. Dalam hal ini, kelompok rentan seperti masyarakat dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental, maupun sensorik belum mendapatkan perhatian khusus.
Fakultas Geografi UGM kembali mengadakan serial diskusi bulanan SDGs yang bertajuk “Literasi dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Difabel” pada Jumat (29/9). “Kita masih perlu bantuan dan refrensi dari negara-negara lain juga ya. Karena kalau dilihat, konteks mitigasi bencana ini sudah banyak upaya yang dilakukan. Tapi untuk difabel, ini saya lihat masih belum dan ini perlu diupayakan bersama-sama. Dan bukan berlebihan kalau Yogyakarta memiliki potensi yang besar. Apalagi dengan mahasiswa yang luar biasa, mereka bisa belajar dengan mendampingi kelompok difabel, seperti ikut membina, mengajarkan, dan sosialisasi terkait kebencanaan dengan peta taktual, misalnya,” tutur Sekretaris Dewan Guru Besar UGM, Prof. Dr. Baiquni, M.A.
Yogyakarta sendiri merupakan salah satu daerah dengan potensi bencana yang cukup tinggi. Beberapa tahun terakhir, bencana seperti gempa, tanah longsor, hingga ancaman tsunami sempat terjadi. Walaupun tidak memakan korban jiwa, namun tahapan mitigasi masih memerlukan evaluasi. Baiquni menambahkan, salah satu upaya yang dapat membantu masyarakat difabel untuk memahami kondisi alam di daerahnya adalah melalui buku panduan.
“Harapannya, nanti akan ada semacam buku panduan ya yang mungkin bisa menjadi bahan diskusi. Buku panduan ini nantinya akan berisi peta taktual, dan juga arahan-arahan khusus bagi masyarakat difabel. Jadi ketika sesuatu terjadi, mereka akan mengerti apa yang harus dilakukan,” tambahnya.
Secara mendasar, terdapat fase-fase penanggulangan bencana yang harus dilakukan, mulai dari kesiapsiagaan hingga tahap mitigasi. Berbeda dengan sebelumnya, penanganan bencana tidak lagi berfokus pada tahapan tanggap darurat setelah bencana terjadi, namun jauh sebelum itu, fokus penanganan harus diprioritaskan pada tahap preventif. “Jadi, ini memang harus diarahkan pada manajemen pra bencana, bukan pada tanggap darurat. Kalau dari segi tanggung jawab, dulu kita melihat kebencanaan ini hanya sebagai tanggung jawab pemerintah, tapi di paradigma sekarang, ini merupakan tanggung jawab bersama. Begitupun dengan manajemen ancaman,” ungkap Prof. Dr. Chatarina Muryani, M.Si. selaku Kepala Pusat Studi Bencana, Lembaga Penelitian dan Penelitian Masyarakat Universitas Sebelas Maret.
Urgensi pendidikan kebencanaan telah muncul di berbagai agenda nasional maupun internasional. Strategi untuk meningkatkan pengembangan mitigasi salah satunya dilakukan melalui pendidikan. Sama halnya dengan kelompok masyarakat lainnya, kelompok difabel juga harus mendapat pendidikan kebencanaan yang memadai. Karenanya, fasilitas penyediaan kebutuhan difabel di sektor pendidikan masih perlu didorong.
Menurut Drs. Setia Adi Purwanta, M.Pd., Direktur Eksekutif Griya Manunggal, pemerintah daerah memiliki peran besar dalam membentuk satuan layanan kebencanaan bagi difabel.
“Pertama itu tetap ada pengutamaan dan inklusivitas. Jadi, semua sama, sama rata. Kemudian ada aksesibilitas melalui akomodasi yang layak. Akomodasi ini itu sebenarnya tidak hanya bagi kelompok difabel. Tapi bagi siapapun yang terhambat informasinya, geraknya itu perlu mendapat prioritas akomodasi. Karena ketika terjadi bencana itu output nya sama. Sama-sama harus tepat dan cepat, padahal kan kondisinya berbeda. Ini problem utamanya,” jelasnya.
Penanggulangan bencana merupakan satu isu yang banyak bersinggungan dengan aspek kemanusiaan. Bencana yang bisa terjadi kapan saja, tentu berpotensi menimbulkan korban jiwa. Sayangnya, tidak semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses informasi kebencanaan, maupun tanggap darurat. Maka dari itu, penting untuk menekankan kembali dalam membuka akses pada masyarakat rentan, seperti difabel.
Penulis: Tasya

